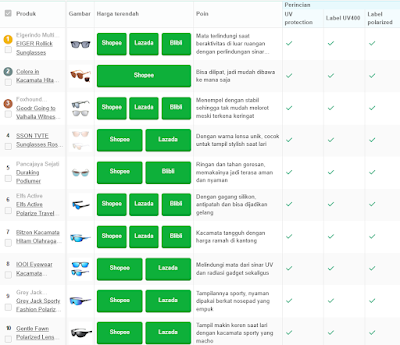|
| Ilustrasi senja di ibu kota, diambil dari sini |
Aku menatap ke luar jendela kaca selebar dinding yang membatasi pandanganku dengan langit Jakarta. Jauh di bawah sana, aku dapat melihat orang yang berjejalan di halte Transjakarta sedang menanti bus yang akan membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Sementara di ufuk barat, mentari tengah bersiap-siap menutup hari, pendar ronanya membias awan.
Sejak dulu aku memang pecinta senja. Selalu ada aura magis yang menyelimuti bumi ketika semburat merah petang menghiasi langit. Namun, inspirasi senja tak lagi dapat kureguk bebas sejak aku pindah ke ibu kota, mengingat setiap sore aku masih terkurung di ruang kerja.
Beberapa penghuni kantor di lantai delapan ini melambaikan tangan padaku dari balik kaca transparan. Meskipun aku tak dapat mendengar ucapan mereka, dari gerak bibir mereka aku paham bahwa mereka tengah berpamitan. Beberapa dari mereka akan segera bergabung dengan keriuhan halte di bawah, yang lain akan meramaikan jalanan ibu kota dengan mobil pribadi, ojol, atau taksol, sebagian larut dalam gegas untuk menumpangi commuter line.
Kehidupan ibu kota memang keras: tiap orang berkejaran dengan waktu mulai subuh hingga malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan untuk mengejar mimpi dan pundi-pundi rezeki. Mungkin hal itu jugalah yang menjadi alasan keberadaanku di sini.
“Belum pulang, Kak?” Sebuah suara yang diikuti dengan paras jelita muncul dari balik pintu. Rara, mahasiswi yang sedang magang di kantor ini, menatapku dengan pandangan bertanya. Di tangannya ada setumpuk berkas, raut wajahnya memancarkan kelelahan.
“Dokumen yang harus kuperiksa?” Aku mengedikkan kepala ke arah berkas-berkas itu. Dia mengangguk sambil tersenyum, kemudian berjalan menuju sudut meja. Dia sudah hafal di mana dia harus meletakkan benda-benda.
“Ra, jangan capek-capek ya. Sudah magrib, pulang sana.” Aku memandang gadis itu. Meskipun letih, semangat masih jelas tergambar di wajahnya. Sama seperti yang banyak kutemui ketika aku melangkahkan kaki di bilangan Sudirman ini, kompleks perkantoran bergengsi yang menjadi tempat kerja impian banyak anak muda.
“Kak, tadi aku ketemu Pak Evan. Beliau titip pesan, kalau pekerjaan sudah selesai, katanya Kakak disuruh menghubungi beliau,” kata Rara sebelum menghilang dari balik pintu. Aku mengangguk, lalu kembali menekuri layar laptop. Namun sejujurnya, pikiranku sudah melayang ke mana-mana.
“Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adrian Evano. Panggil Evan saja, ya,” begitu kalimat yang diucapkannya ketika kami pertama kali bertemu.
“Azalea Pratista, dipanggil Lea,” balasku berusaha sopan.
Sebagai penghuni baru di kantor ini, cukup sulit bagiku untuk langsung menghafalkan nama orang-orang yang kutemui, tetapi tidak dengan sosoknya. Perannya selaku manajer health, safety, and environment di perusahaan manufaktur tempatku bekerja cukup menonjol. Kepribadiannya ramah dan peduli, pekerjaannya selalu rapi, dan dia senantiasa tegas dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya sebagai penyambung informasi perusahaan dengan pihak HSE di lokasi proyek maupun di unit lain.
Menurut kasak-kusuk Rara, tak sedikit perempuan di kantor ini yang menaruh hati pada Evan. Aku tentu tidak heran, mengingat ketampanannya memang berbanding lurus dengan prestasinya. Sebagian dari mereka sering mengajaknya makan siang atau sekadar nongkrong di kedai kopi, tetapi dia selalu menampik dengan alasan sibuk bekerja. Aku hanya bisa terkikik ketika Rara menceritakan itu semua. Kuanggap itu sebagai hiburan, karena memikirkan laki-laki adalah hal paling terakhir yang ada di pikiranku.
Bertahun-tahun aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku berusaha menyibukkan diri dengan beban kerja dan perjalanan dinas, membangun karier, serta berusaha mandiri untuk menghidupi diri, Ibu, dan adikku di Bandung sana. Malam demi malam yang dingin di Kota Kembang kulalui dengan mengambil lembur, berharap kesibukan kerja akan mampu mengusir sepi dan lara hati.
Enam tahun lalu, cintaku dihancurkan berkeping-keping oleh seorang lelaki. Senja kala itu, aku memergokinya tengah berjalan beriringan dengan seorang perempuan, lengkap dengan belaian mesra dan gandeng tangan yang erat. Peristiwa itu membuat pamor senja sedikit tercoreng di mataku.
Aku tak pernah menceritakannya pada Ibu. Yang beliau tahu, aku memutuskan pertunangan dan membatalkan rencana pernikahan secara tiba-tiba. Beliau tak perlu tahu betapa porak-porandanya hatiku, sama seperti ketika Bapak meninggalkan beliau bertahun-tahun silam.
Promosi menjadi manajer quality assurance di kantor pusat membawa perjalananku sampai ke Jakarta. Di satu sisi, aku merasa senang karena dapat membungkus luka yang tersisa dan kabur dari pertanyaan Ibu yang senantiasa menghujani tentang kapan aku akan mengakhiri masa lajang. Namun, di sisi lain aku juga pilu karena merindukan Ibu, adikku, dan kota kelahiran. Tinggal di Jakarta seringkali menggerus kewarasan. Aku merasa tidak punya waktu untuk sejenak melambat dan kadang hal itu membuatku merasa sedikit gila.
“Kamu tidak suka Jakarta?” tanya Evan pada suatu siang. Saat itu aku sedang berjongkok memeriksa ban mobil kantor yang tiba-tiba kempes dalam perjalanan kami menuju Karawang untuk mengecek site pendirian pabrik baru. Perjalanan itu adalah kesekian kali aku bekerja sama dengannya dalam satu tim.
Aku menoleh sekilas ke arahnya, sebelum berseru kepada sopir, “Pak, panggil bengkel saja, ya. Tampaknya ban mobil bocor.”
Evan mengulangi lagi pertanyaannya ketika kami duduk di bangku sebuah warung sembari menanti pihak bengkel datang. Aku memandangnya. “Apa yang membuatmu berpikir begitu?”
“Entah. Kulihat kamu selalu tinggal di kantor sampai larut malam. Datang paling awal, pulang paling akhir. Nggak pernah ikut jalan sama teman-teman,” jawabnya.
Aku bertanya lagi, “Apa yang menarik dari sebuah kota yang panas, bising, berdebu, dan penuh polusi?”
Dia tertawa. Tangannya mengulurkan sebotol teh dingin. “Minumlah dulu, wajahmu merah karena kepanasan.”
Aku membuka botol dan meneguk secercah kesegaran. “Aku kangen Bandung,” kataku.
“Yah, setiap orang dihadapkan pada risiko dalam setiap langkah kehidupan. Tinggal di Bandung mungkin lebih nyaman, tapi karirmu akan begitu-begitu saja. Seperti halnya manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja, semua potensi bahaya dan risiko dikalkulasi, lalu dimitigasi dan dikendalikan. Ada risiko yang masih bisa diterima. Nah, itu yang kita kendalikan dampaknya.”
Aku memandangnya sambil setengah tertawa. “Jadi kita sedang kuliah tentang manajemen risiko di tengah jalanan desa antah berantah?”
Evan terbahak hingga kelihatan susunan giginya yang rapi. “Bukan begitu. Maksudku, dalam hidup ini ada banyak hal yang berjalan tidak sesuai harapan. Itu yang disebut risiko kehidupan. Tapi di balik itu semua, tentu ada hikmah dari promosimu ke Jakarta. Karir naik, gaji juga mengikuti kan?”
“Beban kerja dan tanggung jawabnya juga tidak sedikit,” kilahku.
“Oh, itu jelas,” seru Evan, “tapi kamu juga bisa mencari hal-hal yang membahagiakan dari kehidupan Jakarta. Sebuah alasan di mana suatu hari nanti kamu akan merasa beruntung telah berada di sini.”
Aku hanya mengangkat bahu, belum sepenuhnya menyadari makna kalimatnya.
Proyek pendirian pabrik baru itu memakan sumber daya yang tidak sedikit. Pekan demi pekan kami habiskan untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaannya. Rapat-rapat berlangsung maraton hingga larut malam. Pada suatu akhir hari yang melelahkan, Evan mengajakku berjalan menyusuri Jalan Sudirman di waktu petang. Aku sendiri tak tahu pasti mengapa dengan mudah aku mengiyakan ajakannya.
“Kamu tahu kenapa aku suka Jakarta?” tanya Evan. Aku menggeleng.
Dia melanjutkan lagi, “Kota ini adalah simbol perjuangan dan perubahan. Dinamikanya memang keras, tapi somehow membuat orang-orang di dalamnya menjadi tangguh. Siapa yang tidak bergegas akan tergilas, itulah cara kehidupan mengajari kita akan makna kerja keras.”
Aku manggut-manggut. Setelah sekian lama aku tak merasakan keindahan senja, sore itu menjadi semacam muara bagiku untuk kembali menikmati kemolekannya. Jakarta yang ramai dan bising seakan memendar dalam cahaya jingga. Berkawan sepoinya angin, aku mengurai rindu. Bersama temaramnya sinar surya yang kembali ke peraduan, hatiku menunduk khusyuk dalam syahdu.
Aku menarik napas dalam dengan mata terpejam. “Sudah lama aku tak merasakan indahnya senja seperti ini.”
Ketika aku membuka mata, kudapati Evan tengah menatapku. Binar sandyakala memantul dari matanya. “Kamu suka senja?”
Aku mengangguk sambil berucap, “Pada senja aku menemukan damai. Membuatku berpikir positif, bahwa apa pun yang kulalui hari itu memiliki akhir yang indah sehingga rasa syukurlah yang kurasakan saat menutup hari. Sayangnya aku tak bisa sering-sering menikmati senja sekarang ini. Pekerjaanku tak pernah selesai sebelum magrib.”
Evan terdiam cukup lama. Sejurus kemudian dia berkata, “Oke, mulai besok, kalau pekerjaanmu belum selesai, kita bawa laptopmu ke rooftop. Kamu bisa rampungkan di sana sambil melihat senja. Ada bangku-bangku di ujung helipad yang bisa kita pakai duduk.” Aku terbelalak. Laki-laki ini sungguh penuh kejutan.
Sepanjang jalan kami mengobrol tentang banyak hal. Untuk pertama kalinya setelah enam tahun, aku tak lagi membenamkan diri dalam lubang tak berkesudahan. Kupikir kehidupan Jakarta yang berkejaran, ternyata hati dan pikiranku yang kelelahan. Malam itu, mata dan hatiku terbuka. Semuanya terlihat berbeda.
Pada para pekerja yang tengah menanti bus untuk pulang, aku melihat binar harapan karena sebentar lagi mereka akan bersua keluarga. Beberapa orang yang berlari melintas di area Senayan dan sekelompok orang yang bersorak-sorak di stadion softball mengajariku bahwa seberapapun kerasnya bekerja, kita tetap harus meluangkan waktu untuk self-care. Pada orang-orang yang berkumpul di kedai kopi atau tempat makan, aku memahami pentingnya membangun relasi dan kehangatan di dunia nyata.
Senja hampir saja berlalu ketika ketukan halus terdengar di pintu dan membuyarkan lamunanku. Kudongakkan kepala dan kulihat Evan sudah berdiri di sana dengan senyum yang memesona. “Rooftop?” tanyanya.
Aku tertawa sambil menggeleng. “Rasanya tak perlu, pekerjaanku sudah selesai.”
“Oke, kalau begitu … nasi goreng Jalan Sabang?” tanyanya lagi.
Aku mengangguk dan membalas senyumnya. Setelah membereskan berkas-berkas yang tadi kuperiksa, aku mematikan laptop dan menyambut uluran tangan Evan. Tangan itulah yang menggenggam jemariku dengan hangat di atas jembatan Semanggi, ketika kami menikmati kerlap-kerlip lampu ibu kota pada suatu malam selepas menyusuri Jalan Sudirman. Aku menatap matanya lekat. Kurasa aku sudah menemukan alasan yang membuatku merasa beruntung telah berada di sini.
Tulisan ini diikutsertakan dalam Tantangan Blogging Mamah Gajah Ngeblog bulan September yang bertema “ROMANTISME”.